Ini semua bermula dari sebuah spontanitas. Saat sedang bekerja—dan hari itu, entah mengapa, pekerjaan cepat selesai sebelum matahari tepat di atas kepala. Barangkali karena itu, pikiranku mulai melanglang buana.
Katanya, overthinking harus diblok. Tapi menjadi manusia biasa, mustahil rasanya untuk benar-benar menghindarinya.
Sama seperti teriknya hari ini, perasaanku pun terasa menyengat. Kekesalan tiba-tiba merambat, menggerayangi rongga pikirku—semata karena aku begitu antusias memberikan atensi kecil kepada seseorang. Dasar manusia, masih saja berharap mendapat validasi dengan begitu mudahnya.
Bukan tanpa alasan. Hanya saja, untuk yang satu ini, aku butuh perkembangan—butuh titik terang dari benang merah yang kusut ini.
Sampai di titik ini aku sadar: mengharapkan apresiasi dari seseorang yang penting dalam hidup kita, nyatanya tak pernah mudah. Pernah terlintas, mungkinkah kehadiranku hanya pelengkap? Atau justru rasa sayangku yang terlalu besar—melebihi miliknya padaku?
Aku lalu bercermin, mengukur ulang diriku sendiri. Sudahkah aku memperlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya? Nahasnya, ketika aku menggali lebih dalam, aku mendapati diriku sendiri… jauh lebih kejam dari yang kuduga.
Langit sore ini mendadak berubah kelabu. Begitu cepat, seperti tak memberi waktu. Tapi tak secepat harapanku yang tak kunjung tercapai. Aku melihat orang-orang dengan senyuman yang cerah, dan tiba-tiba muncul pertanyaan itu lagi:
“Apakah mereka juga sama sepertiku? Menunjukkan hal-hal yang indah saja di ruang publik?”
Mengapa aku harus berpikir sejauh itu? Ah… overthinking lagi.
Lucunya, kecepatan tanganku menulis tak pernah sebanding dengan laju pikiran yang menumpuk di kepala. Menyusun kata tak pernah semudah yang orang bayangkan. Ingin rasanya mengungkapkan semua yang terpendam, tapi jujur saja—bibir ini kelu. Seolah hati dan pikiran sedang beradu sengit dalam sunyi, memperebutkan kendali untuk berbicara lebih dulu.
Seharusnya aku bisa jadi nahkoda. Punya kendali penuh atas apa yang ingin aku ucapkan. Tapi kamu tahu kan? Laut lepas memang indah, tapi juga berbahaya. Sedikit saja salah arah, maka ombak bisa melukai.
Jam sudah menunjukkan waktu pulang. Tapi jariku masih menari di atas papan tik, dan mataku menatap keluar jendela berteralis emas. Di sana ada genteng merah, dan pohon hijau yang aku bahkan tak tahu jenisnya. Pemandangan yang sederhana—tapi justru membawaku lebih dalam ke ruang pikirku sendiri.
Andai keberanian yang kupunya tak melukai siapa-siapa, mungkin akan lebih mudah bagiku untuk menyampaikan semua isi hati. Tapi benarkah kejujuranku justru menciptakan jarak?
Kalau nanti hidupku harus berjalan di antara keterpaksaan dan kepasrahan, mungkin satu-satunya jalan adalah hidup untuk diriku sendiri. Karena bukankah, pada akhirnya, manusia akan tetap hidup sendiri?







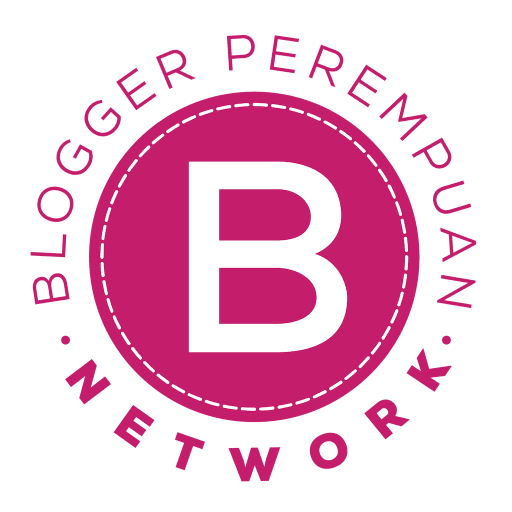

0 Comments:
Posting Komentar